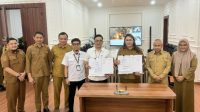Oleh : Ari Loru
Hidup di era serba sat set memiliki tantangan serta anugerah, apakah itu makanan siap saji, atau informasi tersaji. Semuanya hampir mengalahkan kecepatan mata kita berkedip.
Maka seketika itu pula infomasi hadir di hadapan kita.
Tantangan kita di zaman ini ialah bagaimana cara kita mendewasakan kemajuan teknologi, dan anugerahnya bukan terletak pada kecangihan semata, ia mendengar yang jauh, menjaga solidaritas, merawat kehidupan.
Baca Juga: Fery Irwandi, Suara Yang Tak Pernah Padam
Di saat kita merebahkan badan, sambil melepas penat dengan gadget kita, mula-mula merefleksikan fikiran. Tapi nyatanya ketika kita menyaksikan di layar mini melalui platform media sosial kita, saudara kita yang lagi berduka di Tamiang (Aceh) sana, memanggil nama kita dalam lirih doa mereka.
Mungkin raga kita lelah, jiwa kita lesu, akan tetapi hati kita memanggil. Ada tangis yang kita redam, ada luka yang kita usap, bahkan ada air mata untuk kita sembuhkan. Inilah salah satu asbab, membuat Chiki Fawzi memberi senyuman penalar luka bagi Tamiang.
Namanya tidak setenar aktivis lingkungan pada umumnya. Saya pun baru tahu ada wanita hebat rupanya bekerja lirih di kebeningan hati. Suara itu memberi harapan bagi mereka yang berduka.
Baca Juga: Air Mata di Pelepuk Mualem (Muzakir Manaf)
Chiki Fawzi, bernama lengkap Marsha Chikita Fawzi, lahir pada 28 Januari 1989. Ia dikenal sebagai seniman, animator, musisi, sekaligus aktivis sosial.
Ia menempuh pendidikan animasi di Malaysia dan pernah bekerja di industri kreatif internasional sebelum kembali ke Indonesia. Namun di balik latar seni dan karya visualnya, Chiki memilih menjejakkan kaki langsung ke ruang-ruang luka kemanusiaan.
Kehadirannya di lokasi bencana bukan sekadar simbol empati figur publik. Ia datang untuk melihat, mendengar, dan merasakan. Baginya, penderitaan tak cukup hanya dibagikan ulang di media sosial; ia harus disaksikan agar nurani tak mati rasa. Dari sanalah kepedulian menemukan maknanya yang paling jujur.
Baca Juga: Arsenal: Rumah Lama, Luka Baru, Pertarungan Menuju Masa Depan
Aceh Tamiang sendiri mengalami luka panjang. Banjir yang melanda merendam rumah, memutus akses desa, dan memaksa ribuan warga mengungsi. Di banyak titik, air datang bukan hanya membawa lumpur, tetapi juga ketakutan, kehilangan, dan ketidakpastian hidup.
Bagi sebagian warga di pelosok, bencana bukan hanya soal air yang naik, tetapi juga soal bantuan yang tak kunjung tiba. Jalan terputus, komunikasi terhenti, dan kebutuhan dasar menjadi kemewahan. Di sanalah luka sosial tumbuh diam-diam, jauh dari sorotan.
Dari apa yang ia saksikan langsung di lapangan, Chiki Fawzi menyampaikan kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Ia melihat bagaimana tenda-tenda bantuan pemerintah sejauh ini lebih banyak berdiri di sepanjang jalan-jalan besar di ruang yang mudah dilihat, mudah didokumentasikan.
Baca Juga: FALDY BHUCEK, King Tarkam dari Sigi
Sementara di pelosok-pelosok yang lebih sunyi, tempat warga paling lama terisolasi dan paling parah terdampak, kehadiran negara masih terasa jauh. Ada ketimpangan antara pusat perhatian dan pusat penderitaan.
Namun kegelisahan itu tidak berubah menjadi sinisme. Chiki tetap meyakini bahwa harapan untuk semua masih dan harus berada di tangan pemerintah. Baginya, kritik bukan bentuk perlawanan, melainkan panggilan nurani agar negara hadir lebih merata, lebih cepat, dan lebih adil.
Ia percaya, ketika pemerintah mau mendengar suara dari pinggiran dari desa-desa yang tak dilewati jalan besar maka luka Tamiang tak hanya ditutup dengan tenda, tetapi disembuhkan dengan keberpihakan. Negara, dalam keyakinannya, bukan sekadar struktur, melainkan pelindung bagi yang paling rentan.
Baca Juga: Pesan Terakhir
Senyum Chiki di tengah bencana bukan hiasan kamera. Ia adalah bahasa sederhana yang menenangkan. Sebuah cara berkata bahwa duka ini diakui, bahwa penderitaan ini tidak diabaikan, dan bahwa masih ada yang mau tinggal lebih lama dari sekadar singgah.
Teknologi yang sering kita salahkan karena menjauhkan, justru di tangan nurani yang tepat menjadi jembatan. Dari layar kecil, empati membesar. Dari satu suara lirih, kepedulian menemukan jalannya.
Akhirnya, Tamiang mengajarkan kita bahwa bencana tidak pernah benar-benar jauh. Ia hanya menunggu siapa yang mau mendekat.
Baca Juga: Sumpah Pemuda dan Negeri Agraris
Dan lewat senyum Chiki Fawzi, kita diingatkan: luka tidak selalu disembuhkan dengan gemuruh, kadang cukup dengan kehadiran yang jujur, kritik yang berani, dan harapan yang tetap dititipkan pada negara. (*)